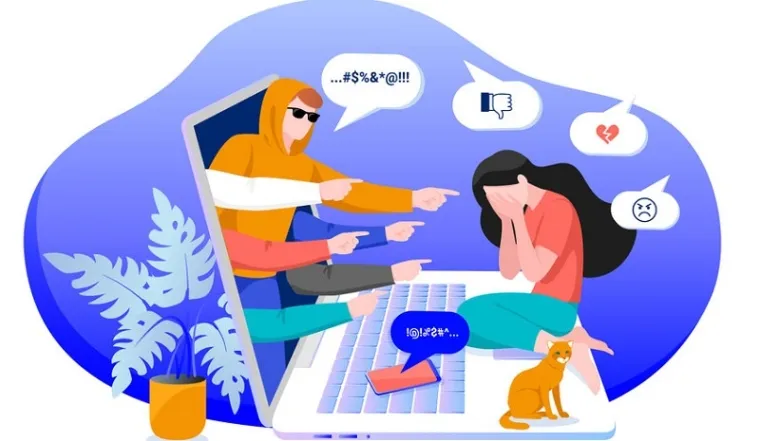DI TENGAH laju pesat transformasi digital, ruang maya telah menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial, ekonomi, bahkan politik.
Namun, seiring manfaatnya yang tak terbantahkan, ruang digital juga membuka pintu bagi hadirnya bentuk kekerasan baru yang sering kali luput dari perhatian.
Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) hadir dalam berbagai bentuk dan kian mengkhawatirkan, terutama karena dilakukan melalui platform digital yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan.
KGBO merupakan bentuk kekerasan yang dilatarbelakangi ketimpangan gender dan terjadi melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau forum daring.
Bentuknya sangat beragam, mulai dari komentar seksis, doxing, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin (revenge porn), penyebaran hoaks yang menyasar identitas gender, hingga pemalsuan konten dengan teknologi deepfake.
Studi oleh Elistya & Arsi (2024) dalam Solidarity Journal menyebut bahwa mayoritas korban kekerasan digital adalah perempuan muda, khususnya pengguna aktif media sosial seperti TikTok dan Instagram.
Salah satu bentuk penyalahgunaan platform digital yang paling merusak adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan.
Konten semacam ini sering kali diunggah oleh mantan pasangan atau bahkan orang asing, dan disebarluaskan melalui grup chat, situs dewasa hingga media sosial mainstream.
Dalam banyak kasus, konten tersebut digunakan untuk mengancam, memeras atau mempermalukan korban.
Penelitian oleh Safela et al. (2023) di Jurnal Dimensi menyebutkan bahwa 73% korban merasa tidak aman menggunakan internet setelah mengalami kekerasan jenis ini.
Penyalahgunaan teknologi juga menyasar privasi dengan cara lain, seperti digital stalking. Melalui fitur lokasi, akses ke media sosial, dan aplikasi pelacak, pelaku dapat memantau aktivitas korban secara terus-menerus.
Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, dampaknya bisa sama merusaknya dengan kekerasan langsung.
Korban mengalami tekanan psikologis berat, ketakutan berkepanjangan, bahkan trauma jangka panjang.
Sayangnya, sistem hukum di Indonesia masih belum cukup progresif dalam mengakomodasi kompleksitas KGBO.
Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi dapat digunakan untuk menjerat pelaku, keduanya belum secara khusus mengatur tentang kekerasan berbasis gender di ranah digital.
Pasal-pasal yang digunakan sering kali multitafsir dan kurang melindungi korban. Bahkan, banyak korban yang justru mengalami reviktimisasi saat mencoba melapor, mereka dianggap “mengundang” kekerasan karena unggahan atau penampilan mereka di media sosial.
Harapan sempat muncul ketika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada tahun 2022.
UU ini menjadi langkah maju karena untuk pertama kalinya, negara mengakui bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik secara eksplisit.
Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara utuh penerapan UU ini terhadap kasus-kasus KGBO.
Seperti yang ditulis Arsyad & Narulita (2022) dalam jurnal Cakrawala Informasi, kurangnya pelatihan dan minimnya kapasitas digital aparat menyebabkan banyak kasus berakhir tanpa kejelasan hukum.
Di sisi lain, peran platform digital sebagai mediator utama dalam penyebaran kekerasan ini belum optimal. Banyak media sosial masih memiliki sistem moderasi konten yang lambat atau tidak responsif terhadap laporan pelecehan dan ancaman.
Anonimitas pengguna, algoritma yang memprioritaskan konten sensasional, serta kurangnya kebijakan internal yang tegas terhadap kekerasan gender, memperparah situasi.
Beberapa platform bahkan tidak menyediakan saluran pelaporan yang ramah korban atau menolak bekerja sama dengan aparat dalam proses hukum.
Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Selain sebagai korban utama, mereka juga kerap menjadi sasaran penilaian moral dari masyarakat.
Media online bahkan sering kali menampilkan narasi yang menyalahkan korban, seperti “mengapa mengunggah foto tersebut?” atau “mengapa membalas pesan dari orang asing?”
Fenomena ini mengakar dari budaya patriarki yang masih kuat di ruang publik dan digital.
Ihsani (2021) dalam Jurnal Wanita & Keluarga menyoroti bahwa victim-blaming menjadi salah satu penghalang utama bagi perempuan untuk berani melapor dan menuntut keadilan.
Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Saat ini, gerakan advokasi berbasis komunitas dan pendekatan feminis mulai menunjukkan dampak.
Banyak organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet, LBH APIK dan Komnas Perempuan mendorong edukasi literasi digital, pendampingan hukum, serta reformasi kebijakan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan adil.
Mereka juga mendesak platform digital untuk bertanggung jawab secara sosial, termasuk dengan melibatkan perempuan dalam tim moderasi konten dan desain fitur keamanan.
Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi. UU ITE perlu direvisi agar lebih berperspektif korban dan tidak digunakan secara diskriminatif.
Pemerintah juga harus mendorong kolaborasi antara kementerian, aparat penegak hukum, platform digital, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem pelaporan yang cepat, aman, dan berpihak pada korban.
Lebih penting lagi, pendidikan literasi digital sejak usia sekolah harus diintegrasikan agar generasi muda memiliki kesadaran kritis terhadap bahaya kekerasan digital dan cara menghadapinya.
Tentu saja, semua upaya ini memerlukan waktu dan komitmen jangka panjang. Namun, jika penyalahgunaan platform digital dibiarkan terus berlanjut tanpa tindakan sistemik, maka bukan hanya korban yang dirugikan, tetapi juga masa depan demokrasi digital yang seharusnya inklusif dan merdeka.
Penutup dari narasi ini adalah satu kesadaran penting adalah bahwa teknologi tidak netral. Ia bisa menjadi alat pembebasan atau penindasan, tergantung pada siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa.
Maka, perjuangan melawan kekerasan gender berbasis online bukan sekadar isu teknologi, tapi juga isu keadilan sosial dan kemanusiaan. (*)
Tugas Kelompok Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia:
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas
- 1. Syifa Aulia
- 2. Nazwa Syahratulafiani
- 3. Mardatilah Rivana
- 4. Adinda Wulandari Lubis
- 5. Muhammad Adittya
- 6. Dhiva Zahra Fadilla
- 7. Nurul Fadhilah Susantri
- 8. Fatikah Turromah
- 9. Faris Putra Rinaldy
- 10. Nopia Musneti
- 11. Nayva Imano
- 12. Cici Famelya Sari
- 13. Nantenaina Claire Balbine
- 14. Salwa Naqhia Syafani
- 15. StevenWilliamTeja
- 16. Fauzan Alfaris
- 17. Taqiya Tsabita Aisyah
Referensi:
Safela, A. W., Mahmud, H., Dewi, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap KBGO. Jurnal Dimensi.
Ihsani, S. N. (2021). VictimBlaming di Media Online. Jurnal Wanita & Keluarga.
Arsyad, J. H., Narulita, S. (2022). Perlindungan Hukum KBGO. Cakrawala Informasi.
Elistya, N. E., Arsi, A. A. (2024). Kekerasan pada Remaja TikTok. Solidarity Journal.
Komnas Perempuan (2023). Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender.
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Editor : Mangindo Kayo