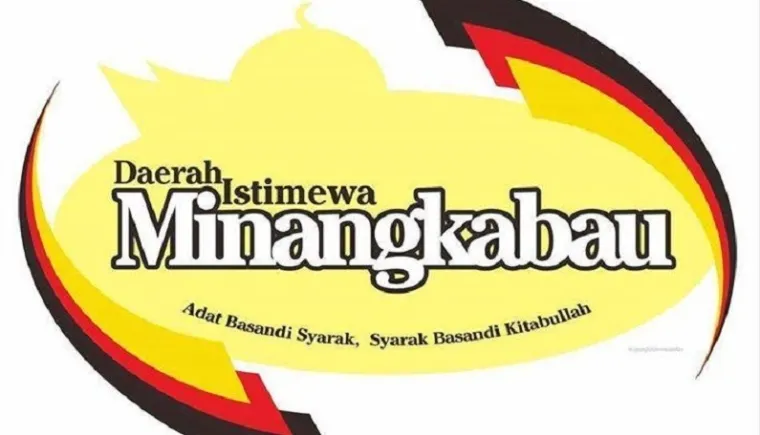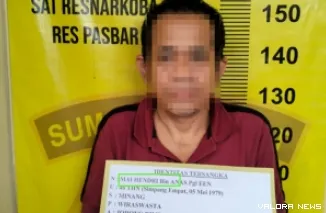Pemerintah daerah Sumatera Barat, misalnya, bisa menggunakan wacana ini untuk meninjau ulang kurikulum muatan lokal, memperkuat lembaga-lembaga adat, serta menata ulang relasi antar nagari agar tak semata menjadi simbol formalitas.
Status istimewa baru akan bermakna jika berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas layanan publik.
Kita harus belajar dari Aceh. Status otonomi khusus yang diberikan pasca perjanjian Helsinki telah membuka peluang luar biasa dalam kebijakan lokal, tapi juga menciptakan tantangan: korupsi elite, konflik internal, dan kesenjangan kebijakan.
Istimewa harus disertai akuntabilitas, bukan hanya simbol kultural.
Juga dari Yogyakarta. Di sana, keberhasilan status istimewa tak hanya karena warisan sejarah, tapi karena pemerintahan Sultan berjalan efektif, merakyat, dan mampu menjadi jembatan antara adat dan modernitas.Sumatera Barat boleh saja berharap, tapi harapan itu harus dibarengi dengan kesanggupan mengelola otonomi yang lebih luas secara adil dan transparan.
Jika tidak, maka ia hanya akan jadi satu lagi gelar administratif yang terdengar indah, tapi hampa makna. (*)