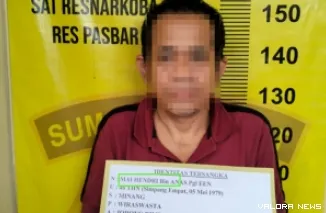Maka, ketika Padang mampu keluar dari jebakan rutinitas administratif dan membenahi layanan dari hulu ke hilir, ada optimisme baru yang layak disambut.
Namun euforia tidak cukup. Sebab tantangan sesungguhnya justru datang setelah penghargaan diterima: bagaimana mempertahankan mutu layanan tanpa bergantung pada stimulus pusat?
Bagaimana menjamin bahwa pelayanan dasar benar-benar menyentuh warga paling pinggiran—bukan sekadar angka-angka di dashboard elektronik?
Dalam beberapa tahun terakhir, Padang melakukan sejumlah terobosan yang patut dikaji. Digitalisasi layanan kesehatan dan pendidikan mulai diterapkan, tidak hanya di pusat kota tapi menjangkau daerah pinggiran seperti Koto Tangah dan Lubuk Kilangan.
Puskesmas diperkuat dengan sistem antrean daring, sekolah-sekolah didorong menggunakan platform evaluasi daring untuk memantau progres siswa.
Ini langkah maju, meskipun masih perlu dukungan infrastruktur yang merata.
Sisi lain yang menarik adalah upaya Pemkot memperkuat pengawasan berbasis masyarakat.Forum warga dan Musrenbang bukan hanya formalitas, tapi mulai dijadikan kanal pengaduan dan monitoring kinerja layanan.
Partisipasi warga menjadi pengingat, bahwa pelayanan publik bukan cuma urusan teknokrat, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat.
Namun, sebagaimana daerah lain di Indonesia, Padang juga tidak kebal dari risiko “SPM kosmetik”—yakni keberhasilan administratif yang tak diikuti perubahan substansial di lapangan.