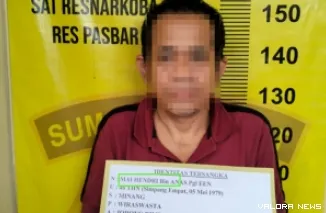Retaliasi bukan hanya persoalan individu. Ia cermin budaya birokrasi yang menolak dikritik, menolak diperbaiki. Ia melanggengkan rasa takut, membunuh semangat perubahan.
DI DALAM banyak institusi, dari dunia korporasi, birokrasi, hingga kampus, tindakan retaliasi sering kali bersembunyi di balik meja rapat dan surat-surat administrasi.
Diam-diam, ia menebarkan ketakutan, menghukum mereka yang berani bersuara, dan membungkam hak-hak yang seharusnya dijamin undang-undang.
Retaliasi—aksi balasan terhadap seseorang karena menggunakan haknya atau mengungkapkan ketidakberesan—bukanlah barang baru.
Ia mungkin tidak selalu berwujud ancaman terang-terangan. Terkadang, cukup dengan satu surat pemanggilan tanpa agenda, satu sidang mendadak tanpa pendampingan hukum, atau satu tuduhan sumir tanpa dasar yang kuat.
Semua itu cukup untuk membuat seorang pekerja, dosen, atau pegawai biasa berpikir dua kali sebelum menuntut keadilan.
Sejarah panjang dunia ketenagakerjaan mencatat, korban retaliasi acap kali adalah mereka yang melaporkan pelanggaran hak, seperti keterlambatan pembayaran upah, diskriminasi, atau pelanggaran kontrak.Alih-alih mendapatkan perlindungan, mereka justru berhadapan dengan serangkaian tindakan yang menyudutkan.
Dipanggil menghadap, ditekan untuk mengundurkan diri, hingga dipecat dengan alasan yang dibuat-buat.
Di Indonesia, perlindungan terhadap korban retaliasi sebetulnya sudah ditegaskan. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha menjatuhkan sanksi atau memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja yang menggunakan hak normatifnya.