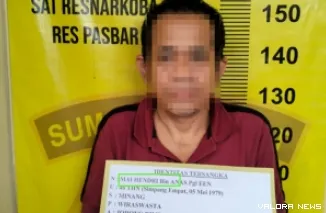Tapi pada saat yang sama, tidak ada transparansi memadai tentang bagaimana dana dikelola dan siapa yang diuntungkan. Ibadah menjadi panggung, dan umat jadi penonton yang terus membayar tiket.
Hubungan dengan Arab Saudi pun sarat negosiasi diplomatik dan ekonomi.
Kuota haji diberikan oleh Saudi, sistem visa digital diatur oleh Saudi, bahkan perusahaan katering dan hotel pun banyak yang dikuasai oleh jaringan bisnis Saudi.
Indonesia, sebagai negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia, tidak memiliki posisi tawar yang sekuat jumlahnya.
Diplomasi haji sering berjalan seiring dengan hubungan politik dan ekonomi dua negara, bukan semata urusan keagamaan.
Dalam praktiknya, jasa haji juga telah menjadi sektor industri. Travel umrah dan haji khusus tumbuh bak jamur di musim hujan.Namun, ini melahirkan ketimpangan baru: yang kaya bisa berangkat berkali-kali melalui jalur khusus, sementara yang miskin menunggu antrean 20 tahun.
Privatisasi sebagian layanan haji tidak serta-merta menghadirkan keadilan. Justru makin memperlebar jurang antara “jamaah VIP” dan “jamaah reguler.”
Sayangnya, diskursus publik soal haji nyaris selalu dikurung dalam pertanyaan fikih: sah atau tidak, halal atau haram, sesuai syariat atau bid’ah.
Sangat jarang dibuka ruang kritis untuk membahas pertanyaan kebijakan: apakah pengelolaan haji adil, transparan, dan akuntabel? Apakah benar ibadah ini dikelola semata-mata untuk kemaslahatan umat?