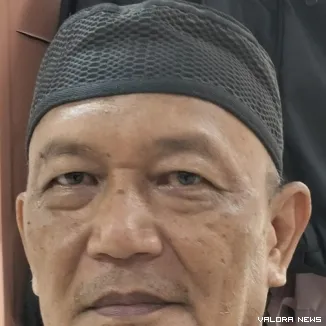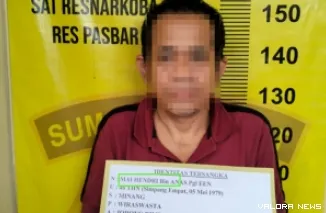Sayangnya, tafsir ibadah ini sering kali hanya berhenti pada gerakan, bukan pada makna. Di sinilah letak persoalannya.
Haji yang semestinya menjelma revolusi spiritual dan sosial, justru direduksi menjadi wisata religi tahunan yang prestisius.
Kita kerap menyaksikan orang-orang yang sebelum berangkat haji begitu religius dalam persiapan—ikut manasik, rajin ke masjid, bahkan belajar fiqih lebih tekun.
Tapi, sekembalinya ke tanah air, kembali juga kebiasaan lama: bisnis licik, bicara kasar, bahkan cenderung makin arogan karena merasa sudah “lulus ibadah paling tinggi.”
Maka, gelar "Haji" menjadi seperti ornamen status sosial baru, bukan jejak transformasi spiritual.
Padahal dalam konteks sosial, ibadah haji bukan sekadar ritus vertikal antara manusia dan Tuhan. Ia punya dimensi horizontal yang sangat kuat.
Ketika Rasulullah menyebut bahwa haji mabrur tak lain balasannya surga, ia menyambungnya dengan syarat: tidak rafats (ucapan jorok), tidak fusuq (perilaku durhaka) dan tidak jidal (bertengkar).Artinya, syarat diterimanya haji bukan hanya menyelesaikan rangkaian manasik, tetapi menjadikan ibadah itu sebagai batu loncatan perubahan laku sosial.
Namun realitas di Indonesia menunjukkan gejala sebaliknya. Menurut Kementerian Agama, Indonesia adalah pengirim jemaah haji terbesar di dunia—lebih dari 240.000 orang per tahun.
Tetapi angka itu tak berbanding lurus dengan kualitas etika sosial masyarakat Muslim di dalam negeri.