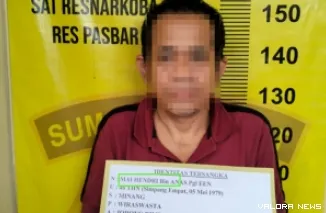“Menjawab wawancara bukan kejahatan digital,” kata sang ahli. “Kalau pun mau dikenai pasal, mestinya KUHP, bukan UU ITE.”
Penjelasan ini bukan sekadar teknis. UU ITE dirancang untuk mengatur perbuatan baru yang lahir dari teknologi digital—seperti peretasan, penipuan daring, atau penyebaran konten ilegal melalui sistem elektronik.
Menggunakan pasal ini untuk membungkam pernyataan di sebuah wawancara lisan sama saja memperluas yurisdiksi UU ITE melampaui niat pembuatnya.
Truth as Defence
Di banyak yurisdiksi, prinsip truth is an absolute defence of libel—kebenaran adalah pembelaan absolut—adalah fondasi hukum pencemaran nama baik. Jika yang disampaikan adalah fakta, tuduhan pencemaran menjadi gugur.
Sang whistleblower mengklaim semua yang ia sampaikan adalah data dan fakta terkait dugaan korupsi.Jika terbukti, tuduhan terhadapnya otomatis batal. Sebaliknya, jika ini benar-benar fitnah, pembuktiannya harus melalui pemeriksaan kasus utama terlebih dahulu.
Bukan Kasus Tunggal
Fenomena kriminalisasi whistleblower bukan hal baru. ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat setidaknya 12 kasus serupa dalam lima tahun terakhir, di mana pelapor kasus korupsi justru menjadi tersangka.
Kasus Baiq Nuril di Lombok—meski berbeda konteks—menjadi contoh betapa UU ITE bisa digunakan untuk membalik posisi korban menjadi pelaku.